Dentuman-dentuman tabuh memecah keheningan malam sehingga burung-burung yang tengah beristirahat mulai meringik dan terkantuk-kantuk mencari tempat yang aman untuk mengulang aktivitas yang terganggu tadi. Hewan nokturnal lainnya tampak biasa saja ketika bunyi-bunyi memekakkan telinga itu terus-terusan terdengar tanpa ampun.
Per sekian detik, gemuruh dan kilat menghampiri malam yang dapat dikatakan tidaklah baik-baik saja. Angin malam yang biasa mampu menghipnotis seseorang sehingga tertidur, kembali menjelma menjadi angin gila, berubah-ubah arahnya seperti otak manusia ketika terjadi masalah yang diharuskan memilih antara hidup atau mati.
Tukang tabuh berhenti menabuh, gemuruh dan kilat pun ikut berhenti menyapa malam. Kilat-kilat yang tadinya menjilat langit malam, tidak lagi tampak. Tidak ada lagi liuk-liuk di langit, tidak ada lagi cahaya-cahaya api yang ditakuti oleh sebagian anak manusia. Benar-benar tenang walaupun hewan nokturnal mulai bersuara untuk menunjukkan kemerdekaan mereka.
Hujan yang telah reda telah digantikan oleh rinai pembasuh luka, membuat beberapa orang yang tengah mendudukkan diri di pelantar rumah Gadang mulai menarik napas lega. Tampaknya, alam sudah mau berteman dan bersahabat dengan mereka yang memang berharap momen tersebut.
Seorang pria paruh baya yang menggunakan baju kebesaran, anggap saja baju penghulu atau datuk pada zaman dulu, terlihat menuruni anak tangga rumah Gadang. Tongkat yang digunakan sebagai salah satu pemisah antara yang berpangkat dan tidak, digenggam erat untuk menyeimbangi langkah yang telah goyah karena lutut bergetar dimakan oleh waktu dan pengalaman.
Setelah menginjakkan kaki di lantai dasar, ia mendongak, melihat langit yang masih menangis, menumpahkan air mata kegelisahaan walaupun sedikit dan tidak banyak. Lalu, pria paruh baya itu melihat ke arah samping, tepatnya pelantar, sambil tersenyum canggung.
Salah satu wanita yang menggunakan baju bundo kanduang lengkap dengan tingkuluak, lambak, baju batabue, serta minsle, menghampiri pria paruh baya yang kemungkinan merupakan suaminya. Ia memberi salam dengan mengatup kedua tangan sambil menundukkan kepala dalam.
“Tuhan Allah menegur kita semua yang jarang bersyukur akan segala nikmat dengan cara menumpahkan air sungai dari langit. Sepeluh hari langit menangis kuat disertai angin gila, membuat siapa pun benar-benar menunduk dalam untuk merenungi kesalahan yang ada. Alih-alih menyalahkan antar sesama, alam benar-benar menyadarkan kita akan kesalahan sendiri,” kata pria tua itu, kemudian menghela napas dalam.
“Tabuh di rumah Gadang telah ditabuh dengan kuat, tentu bakaua harus dilaksanakan secepatnya untuk meminta perlindungan Allah. Hitung-hitung Allah melindungi kita dari segala marabahaya dan bencana setelah hujan besar ini. Tidak masalah gagal panen, setidaknya jangan ada longsor atau banjir,” ungkap wanita yang menggunakan baju kebesaran itu.
Pria tua yang bergelar Datuk Rajo Gadang, biasa dipanggil datuk atau penghulu untuk menyiratkan kedudukkan dirinya di kalangan masyarakat, mengangguk pelan, meminta semua orang berkumpul. Ia menyampaikan pitatah-pititih yang memang sudah melekat turun-menurun di kalangan masyarakat Minang.
Panglima serta pembawa kabar, kedudukkan yang di bawah penghulu, yang telah mendapat perintah dari Datuk Rajo Gadang pergi ke rumah warga, menyampaikan berita penting tersebut. Bukan dengan cara mendatangi satu per satu rumah warga, mereka menggunakan suara keras serta talempong untuk membangunkan mereka. Tentu suara keras tersebut berisi berita penting tersebut.
Pagi-pagi sekali, semua warga telah berkumpul, baik yang muda dan tua, anak-anak dan dewasa, hingga sesepuh desa, telah berada di halaman rumah Gadang. Mereka mengenakan pakaian rapi karena tahu akan ada acara bakaua. Tampak ibu-ibu membawa nampan yang berisi makanan serta hasil ladang walaupun tidak seberapa.
Datuk Rajo Gadang beserta istri keluar dari rumah Gadang yang memiliki sembilan bilik itu dengan anggun. Bukan pakaian kebesaran seperti pada umumnya digunakan oleh datuk, mereka menggunakan pakaian sederhana, baju kurung berwarna putih. Terlihat istri sang datuk menggunakan tudung.
Di halaman rumah Gadang yang memiliki rangkiang berjejer, masyarakat berbaris sesuai aturan yang telah disepakati. Dubalang terlihat membawa anglo yang berisi arang untuk acara tersebut. Ia mendekat, memberikan benda kecil tersebut kepada Datuk Rajo Gadang.
Istri dari Datuk Rajo Gadang mengambil dan menaburi anglo tersebut dengan kemenyan gunung dan arab. Bau harum pun menguar, mengusik indra penciuman. Sungguh wangi seperti malaikat yang baru turun dari langit kata-kata orang dahulu yang merujuk pada wewangian pekat.
Mereka semua mulai melangkah dengan nyanyian serta petuah-petuah lama yang mungkin jarang sekali didengar oleh telinga. Di barisan depan, sang datuk memutar anglo searah jarum jam serta merapal beberapa kata sakral, di barisan ibu-ibu menjawab pelan kata-kata sakral tersebut, sedangkan di barisan belakang sekali, bapak-bapak menabuh tabuh dengan kuat, menciptakan bunyi sumbang, tetapi enak didengar.
Satu jam mengelilingi kampung yang terkesan sunyi dan sepi itu, tidak ada yang mengeluh walaupun sudah penat melangkah dan membawa beban, langkah mereka sampai di tanah lapangan yang benar-benar lenyah. Semua beban yang mereka bawa, diletakkan dan dijejerkan.
Terlihat hal tersebut terkesan seperti memberi sesembahan kepada alam, padahal di lapangan tersebut tidak ada pohon atau batu besar. Sejujurnya, lapangan tersebut hanya menghadap ke arah dua gunung, Gunung Merapi dan Gunung Singgalang. Itu pun terkesan sangat jauh dalam pandangan, seperti pepatah yang sering didengar, Gunung Merapi sebesar telur itik.
Anglo yang masih mengeluarkan asap, seperti mengeluarkan harapan untuk hari esok mengenai keadaan sesungguhnya, diletakkan ke arah tengah oleh dia yang dihormati atas gelar dan kedudukkannya di tengah-tengah masyarakat yang patuh akan tradisi dan budaya.
Datuk Rajo Gadang beserta istri mendudukkan diri, membiarkan baju putih itu kotor akan lenyah. Mungkin, tidak banyak pemimpin yang mampu mendudukkan diri bersama rakyat mereka, apalagi tempat tersebut kotor. Hal tersebut pun diikuti oleh yang lain.
Tidak ada perintah, tidak ada suruhan, tidak ada suara, dan tidak ada kata, mereka semua menunduk dalam sambil menakup kedua tangan kuat. Langit mendung yang tampaknya akan mengeluarkan tangis, diwakili oleh mereka semua. Satu per satu dari mereka berdoa sambil menangis, memohon ampun atas dosa yang telah mereka perbuat.
Tidak bersyukur atas nikmat Tuhan dan tidak bersedekah ketika diberi kelebihan hidup, membuat mereka benar-benar merenung akan teguran Sang Maha Agung. Terlihat dari mereka tidak ada yang menyalahkan siapa pun. Mereka benar-benar intropeksi diri.
“Kita semua merupakan makhluk lemah yang diciptakan oleh Allah. Karena diberi akal, hawa nafsu, dan telah ditunjuk sebagai khalifah oleh Allah di muka bumi, terkadang sikap kita semena-mena terhadap alam. Rakus, ingin menang sendiri, egois, saling menyalahkan tanpa intropeksi, sering kita lakukan sehingga alam dan Allah murka.”
Kalimat pengantar yang disampaikan oleh sang datuk, membuat semua tertegun. Tidak ada yang salah, hal tersebut nyata adanya. Karena nafsu dan ego manusia, terkadang tradisi-tradisi yang telah dibangun dan dikokohkan bersama, hilang bak ditelan bumi. Mereka berdalih bahwa itu adalah haram tanpa mencari dahulu apakah itu benar-benar haram menurut ajaran mereka.
“Bakua sudah kita lakukan untuk menolak bala, tinggal makan bajamba yang akan kita laksanakan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada nikmat hidup. Tidak lupa juga, nanti malam, kita akan melakukan serangkaian upacara adat untuk memperkuat tradisi-tradisi yang telah ada agar tidak dilupakan oleh anak kemenakan kita di kemudian hari,” tambah Datuk Rajo Gadang yang langsung mendapat anggukan dari mereka semua.
Datuak Rajo Gadang berdiri, diikuti oleh mereka semua. Pria tua yang tidak lagi tampan itu tersenyum, membuat kerutan-kerutan di wajah terlihat dengan jelas. Ia mendeham, membuat sang istri paham dan maju selangkah. Tentu setelah datuk menyampaikan petuah, giliran bundo kanduang agar imbang petuah tersebut.
“Minangkabau kental akan tradisi dan kebudayaan. Maka dari itu, adat basandi syarak, syarak basandi kitabulloh merupakan pegangan kita semua untuk menjaga segala hal yang berkait dengan adat dan agama. Di tanah leluhur ini, ambo selaku bundo kanduang untuk anak-anak semua, berhatap tradisi dari tanah leluhur ini tidak hilang walaupun zaman akan menenggelamkan mereka sehingga menyebut tradisi-tradisi ini kuno dan tidak layak lagi. Atau mungkin dipandang haram karena tidak sesuai dengan syariat yang ada.”
“Perlu anak-anak dan sanak saudara ingat. Jika niat di hati memang benar untuk menunjukkan kekuasaan serta bentuk rasa syukur kita terhadap Sang Maha Kuasa, tidak ada salahnya kita melakukan bakua dan makan bajamba. Sekiranya, petuah kecil ini mendapat tempat yang paling dalam di hati sanak saudara semua. Kebenaran itu datang dari Allah, kesalahan itu datang dari kita makhluk Tuhan,” termasuk ambo.
Petuah yang disampaikan oleh sang bundo kanduang dengan nada tenang dan khidmat itu, tampaknya mendapat restu dari alam. Terlihat langit mendung sedikit demi sedikit menghilang, menampakkan sinar mentari pada hari itu. burung-burung kecil yang kedinginan di sangkar, bersiap-siap melakukan peregangan kecil untuk mencari makanan.
Seorang gadis mengerjap beberapa kali karena guncangan dari seseorang. Kemungkinan mimpi indah yang didapat membuat gadis itu susah membedakan realita dan halusinasi. Ia menoleh, kemudian tersenyum saat sang dosen memberikan tatapan yang sulit diartikan.
“Apakah materi yang saya ajarkan seperti lagu pengantar tidur olehmu, Put?” tanya dosen tersebut, lalu berjalan ke arah depan.
“Tidak, Pak. Materi yang Bapak ajarkan tampaknya menjadi mimpi yang indah ketika aku tidak sengaja tertidur. Apalagi, perihal yang Bapak tulis mengenai bakua dan makan bajamba,” ungkap mahasiswi yang bernam Putri itu.
“Tampaknya tanah leluhur terpaksa berpesan melalui alam mimpi kepadaku mengenai tradisi yang telah punah. Ia meminta agar kita gerenasi penerus tidak melupakan hal tersebut karena perkembangan zaman.” imbuh gadis itu, membuat sang dosen tersenyum kecil.
Tampaknya gadis itu benar-benar belajar bahwa tanah leluhur menyimpan satu juta cerita indah. Akan tetapi, cerita itu hilang ditelan oleh bumi karena kesalahan penerus dari tanah leluhur itu sendiri.
-Selesai-
Fote note!
Tingkuluak: Penutup kepala berbentuk runcing atau lonjong.
Lambak: Sarung atau songket yang digunakan dalam pakaian adat Minang.
Baju batabue: baju kurung atau tunik panjang yang melambangkan kekayaan alam Minangkabau
Minsle: Hiasan pada bagian leher dan tepi lengan.
Bakaua: Dilakukan oleh masyarakat zaman dahulu dengan berkeliling kampung, membaca doa bersama sambil membakar kemenyan sebagai bentuk bahwa masyarakat merupakan makhluk lemah bagian dari alam.
Makan bajamba: makan bersama-sama.

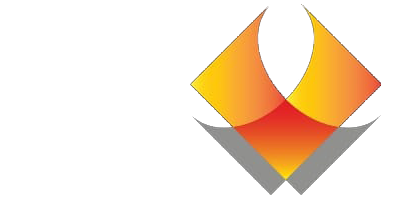


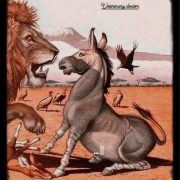








Comments