Apa pun yang berlebihan dalam kehidupan ini niscaya akan menimbulkan mudarat. Tidak terkecuali berlebihan dalam beragama. Sikap berlebih-lebihan alias fanatisme dalam beragama tidak lain merupakan bibit dari radikalisme dan ekstremisme yang mendorong manusia bertindak intoleran bahkan destruktif.
Dalam kitab al-Shahwah al Islamiyyah, ulama Yusuf al Qardlawi menyebut setidaknya lima ciri seseorang telah bersikap fanatik (berlebihan) dalam beragama. Pertama, cenderung bersikap taklid buta pada satu pendapat dan menafikan pendapat yang lain. Tidak jarang, individu atau kelompok lain yang berbeda pendapat dilabeli dengan cap sesat, bidah, kafir dan stigma buruk lainnya.
Kedua, mewajibkan perkara tidak wajib, dan mengharamkan sesuatu yang sebenarnya mubah (boleh) di dalam Islam. Di saat yang sama, kaum fanatik juga kerap membesar-besarkan perbedaan-perbedaan kecil menyangkut praktik peribadatan atau keagamaan.
Ketiga, bersikap intoleran, arogan dan agresif dalam menyikapi perbedaan. Perilaku ini tidak jarang berakhir pada tindakan teror dan kekerasan pada kelompok lain.
Keempat, berprasangka negatif pada kelompok lain dan cenderung bertindak manipulatif, yakni menutup kelemahan atau kesalahan kelompoknya sembari mengumbar kesalahan kelompok lain. Kelima, mudah melabeli kelompok lain sebagai sesat atau kafir bahkan menghalalkan darah orang atau kelompok yang dianggap menyimpang. Inilah puncak dari sikap fanatik dalam beragama yang sangat berbahaya.
Dari paparan Syekh al Qardlawi di atas, kiranya bisa disimpulkan bahwa fanatisme, radikalisme dan ekstremisme memiliki keterkaitan dan saling berkelindan satu sama lain. di satu sisi, sikap fanatik merupakan pengejawantahan nalar radikal dalam tataran paling ringan. Fanatisme dengan demikian ialah bibit dari radikalisme. Di sisi lain, fanatisme yang disikapi secara permisif akan memunculkan keyakinan dan dorongan untuk memusuhi, bahkan menyerang kelompok lain.
Fanatisme Agama dan Kekerasan Struktural
Radikalisme dan ekstremisme memang tidak selalu mengejawantah ke dalam praktik kekerasan langsung (direct violence). Ada kalanya, radikalisme dan ekstremisme juga mewujud ke dalam praktik kekerasan verbal dan simbolik, seperti penghinaan atau pelabelan negatif terhadap individu maupun kelompok tertentu. Dalam istilah Johan Galtung, kekerasan verbal dan simbolik itu disebut sebagai kekerasan kultural (cultural violence). Kekerasan kultural, bagaimana pun juga tidak kalah berbahayanya dengan kekerasan fisik (langsung). Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kekerasan kultural mampu meretakkan sendi-sendi persaudaraan dan persatuan bangsa.
Meski mengusung ideologi kekerasan, radikalisme dan ekstremisme agama tidak harus selalu dilawan dengan pendekatan kekerasan juga. Dalam konteks jangka pendek, penanggulangan radikalisme dan ekstremisme memang harus bertumpu pada pendekatan keamanan. Namun, dalam konteks jangka panjang dibutuhkan strategi kultural untuk menghalau radikalisme, ekstremisme dan fanatisme.
Strategi Melawan Ekstremisme, Radikalisme, dan Fanatisme
Strategi kultural ini harus melibatkan setidaknya tiga sudut pandang, yakni psikologis, sosiologis dan teologis. Dari sisi psikologis, setiap individu perlu mengembangkan karakter open minded (berpikir terbuka). Dengan berpikir terbuka, diharapkan akan muncul kesadaran bahwa perbedaan opini merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan. Hal ini penting lantaran fanatisme sebagai embrio radikalisme dan ekstremisme kerap dilatari oleh problem psikologis individu. Seseorang dengan karakter close minded (berpikir tertutup) cenderung mudah terjebak pada fanatisme.
Dari sisi sosiologis, diperlukan sebuah inisiatif untuk membangun ruang publik yang inklusif dan demokratis dimana setiap entitas memiliki hak yang setara untuk mengaktualiasasikan diri. Ruang publik berbasis pluralisme budaya dan agama ini akan melahirkan jejaring masyarakat sipil yang berkarakter toleran. Soliditas masyarakat sipil (madani) dengan karakter inklusif, toleran dan pluralis itu niscaya akan menutup celah bagi berkembangnya radikalisme dan ekstremisme.
Terakhir, dari sisi teologis kita perlu membumikan ide peacebuilding (bina-damai) dan non-violent movement (gerakan nir-kekerasan). Seperti kita tahu, praktik keberagamaan yang berlebihan (ghuluw) dan pengidolaan berlebihan pada tokoh (ithrah) kerap melatari munculnya politik kebencian dan kekerasan berbasis agama. Maka, disinilah pentingnya membangun model keberagamaan yang damai dan anti-kekerasan.
Di era kontemporer ini, tantangan terberat bagi bangsa dan negara bukanlah kolonialisme, krisis ekonomi atau hal-hal sejenisnya. Alih-alih itu, tantangan terbesar kita ialah mewabahnya fanatisme, radikalisme dan ekstremisme beragama. Dampak ketiga paham itu sangat terasa dalam kehidupan ekonomi, politik terlebih agama. Adalah tanggung jawab bersama untuk menghalau ketiga paham itu sejauh mungkin dari kehidupan beragama dan bernegara

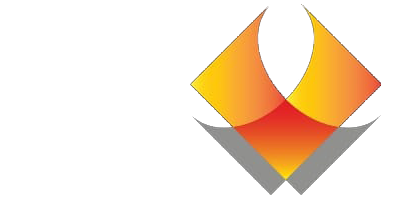









Comments