Lima tahun berlalu sejak teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Rakyat Indonesia pun sudah banyak yang tahu dan bangga karena mereka tidak lagi dijajah oleh bangsa Eropa, Negara Belanda, maupun Negara Jepang. Kendati demikian, pembangunan belumlah merata pascapenjajahan. Maka dari itu, untuk mengurangi jumlah penduduk di Pulau Jawa dan melakukan pemerataan dalam beberapa sektor, pemerintah pusat ingin melakukan program transmigrasi yang sempat tertunda pada Zaman Kolonial. Tentu hal ini sejalan dengan penuturan Wakil Presiden Mohammad Hatta yang menyebutkan pentingnya transmigrasi untuk mendukung pembangunan Industrialisasi di luar Jawa.
Darmono terduduk dengan surat kecil yang ada di tangan. Perintah untuk transmigrasi ke Pulau Sumatra, lebih tepat Lampung, sudah diterima oleh pria yang sudah berusia 26 tahun itu. Helaan napas begitu luruh, rasa bimbang dan juga waswas hadir tanpa diminta, serta rasa gundah pun menyeruak, memenuhi alam bawah sadar Darmono. Ia bingung untuk memberi tahu sang ibu mengenai isi surat itu.
“Ada apa Darmono? Kenapa wajahmu seperti itu?” Seorang wanita tua yang menggunakan pakaian sederhana keluar dari dalam rumah. Ia membawa secangkir kopi dan sepiring ubi rebus. Diletakkan kedua makanan ke meja kecil yang terbuat dari kayu, ia pun duduk, berhadap-hadapan dengan Darmono.
Di satu sisi, Darmono yang mendengar suara sang ibu, langsung menyembunyikan surat ke saku celana. Pria itu memperbaiki posisi duduk, lalu menata kembali makanan yang sudah disusun oleh sang ibu di meja. Ubi rebus pun diambil dan dicicipi oleh Darmono. Tidak lupa, ia juga mengambil ubi yang tidak lagi panas dan memberikannya kepada sang ibu.
“Ada apa? tanya Sakdah, ibu Darmono, sambil menerima pemberian sang anak.
“Tidak ada apa-apa, Bu. Bagaimana pekerjaan Ibu hari ini di kebun Pak Tarno? Apakah lancar atau ada gangguan?”
“Alhamdulillah lancar, Nak. Ibu juga sudah dapat upah dari Pak Tarno,” jawab Sakdah, lalu memasukkan satu potong ubi rebus ke mulut.
Darmono tersenyum saat mendengar jawaban sang ibu. Pria itu merogoh saku baju, mengambil beberapa lembar uang dari upah yang didapatnya ketika jadi buruh bangunan, lalu memberikannya kepada sang ibu. Ia meminta wanita itu untuk berbelanja barang harian dan juga menabung. Setelah itu, Darmono kembali terdiam, memikirkan surat perintah yang membuat otaknya kacau.
“Nak,” panggil Sakdah, membuat lamunan Darmono buyar, “apakah benar kamu baik-baik saja?”
“Aku baik-baik saja, Bu,” jawab Darmono, lalu tersenyum. “Ya sudah, karena malam ini ada jadwal meronda, aku pergi dulu. Ibu jaga rumah. Jika terjadi apa-apa, Ibu jangan lupa teriak.”
Darmono meminum kopi yang belum disentuh sama sekali dengan sekali tenggak. Sambil bangkit, ia menyeka mulut yang basah dengan punggung tangan. Setelah berpamitan dan mencium tangan sang ibu, Darmono masuk rumah, mengambil sarung. Ia pun berlalu dengan sesekali melihat ke arah belakang. Lebih tepat ke arah sang ibu yang masih setia duduk di teras rumah.
Dua hari berlalu, tetapi Darmono belum memberi tahu sang ibu bahwa dirinya berada di nama-nama orang yang ikut program transmigrasi. Rasa bimbang terus-terusan hadir, membuat pria itu tidak fokus bekerja. Hal itu terlihat jelas saat Soleh memanggil Darmono, tetapi tidak ada jawaban. Jangankan jawaban, sahutan atau dehaman pun tidak keluar dari mulut Darmono.
“Oi, Darmono!”
Darmono terperenjat dan langsung menoleh. Ia mengusap dada dengan cepat, melihat Soleh yang sudah ada di hadapannya. Sambil melangkah ke arah tumpukan kayu, ia bertanya alasan Soleh memanggil dengan nada tinggi.
“Bagaimana tidak berteriak, panggilan pelan saja tidak kamu hiraukan,” celetuk Soleh, membuat Darmono terkekeh. “Aku perhatikan dalam dua hari ini, kamu tidak fokus bekerja. Ada apa? Apakah ada yang membuatmu risau?”
Darmono membuka topi yang dikenakan sambil menghela napas dalam. Surat kecil yang selalu dibawa agar tidak ditemukan oleh sang ibu, dikeluarkan dari dalam saku celana, Darmono pun memberi tahu penyebab dirinya menjadi kacau dalam dua hari belakang.
Soleh mengambil dan membaca surat dengan aksara Jawa itu. Dengan wajah serius, ia manggut-manggut, seperti paham isi yang tertera di sana. Setelah itu, ia lipat kembali kertas itu ke bentuk semula dan diberikan kepada Darmono. Ia mengusap dan menepuk-menepuk pundak sang teman dengan pelan.
“Saranku, lebih baik beri tahu ibumu mengenai surat itu. Aku yakin beliau setuju karena ini untuk kebaikan bersama. Apalagi, kamu pergi bukan atas kemauan sendiri, tetapi suruhan dari pemerintah pusat,” nasihat Soleh.
“Aku tidak tega memberi tahu ibuku mengenai ini, Soleh. Aku takut ia tidak rela dan semakin sakit. Apalagi, ibuku hanya memiliki aku sebagai sandaran dan pegangan hidup,” tutur Darmono, mengusap wajah gusar dan menghela napas berkali-kali.
Soleh yang mendengar itu pun tidak bisa berbuat apa-apa. Berbicara mengenai perpisahan sangatlah tidak menyenangkan, apalagi dengan keluarga sendiri. Ia meminta sang teman bersabar dan berdoa, semoga keajaiban datang dengan sendirinya.
Siang beranjak sore. Darmono yang sudah selesai bekerja dan menerima upah harian, berencana menjemput sang ibu di rumah Pak Tarno. Pada saat itu, ia berencana untuk memberi tahu sang ibu mengenai kebenaran yang terjadi. Entah bagaimana reaksi sang ibu, ia tidak ambil pusing karena hari keberangkatan semakin dekat. Di tengah perjalanan, Darmono bertemu dengan Tarno dan beberapa pemuda desa yang dikenalinya.
“Selamat sore, Pak Tarno. Bapak mau ke mana bersama yang lain?” tanya Darmono sopan setelah bersalaman dengan Tarno.
“Aku disuruh oleh Pak Lurah untuk mengumpulkan pemuda yang akan berangkat ke Lampung,” jawab Pak Tarno, lalu melihat kertas kecil yang ada dalam genggamannya. “Di sini ada namamu, Darmono. Apakah kamu ikut dengan rombongan pertama?”
Darmono terdiam sambil tangan mengusap-usap tengkuk. Pria itu menoleh ke arah lain dengan perasaan tidak menentu. Beberapa kali menghela napas, ia tersenyum hambar dan mengangguk, lalu memberi tahu Tarno bahwa dirinya ikut dalam rombongan pertama.
“Ya sudah, lebih baik kita pergi,” usul Tarno yang dianggukkan oleh mereka semua.
Darmono duduk menyendiri di teras ujung sambil menatap langit malam yang tidak dihiasi oleh bulan maupun bintang. Udara dingin yang hadir, tidak membuat Darmono beranjak selangkah pun untuk pindah ke dalam rumah. Baru saja mengambil lipatan surat dari saku, pria itu tersentak saat mendengar suara sang ibu yang memanggilnya dengan lembut.
“Ibu sudah tahu jika kamu dipindahkan ke Lampung oleh pemerintah pusat,” ucap wanita tua itu, lalu tersenyum hambar.
“Akan tetapi, aku tidak ingin pergi dan meninggalkan ibu seorang diri di sini. Apalagi, ibu sering sakit. Siapa yang merawat ibu ketika sakit nanti?” ucap Darmono sambil meraih dan menggenggam kedua tangan sang ibu. Air mata Darmono luruh melihat wajah tua Sakdah yang sudah keriput.
“Doakan saja ibu baik-baik di sini, Nak,” ungkap Sakdah, melepaskan salah satu tangan dari genggaman anaknya, lalu mengusap air mata yang membasahi pipi Darmono. “Bukankah kamu tahu bahwa keputusan dan kebijakan pemerintah merupakan hal yang baik.”
“Memisahkan anak dengan orang tuanya bukanlah hal yang baik, Bu,” jawab Darmono dengan sesak di dada.
Sakdah tersenyum kecil mendengar penuturan Darmono. Ia yang sudah bertanya-tanya kepada Pak Lurah dan Tarno mengenai program transmigrasi untuk penduduk Pulau Jawa, memberi tahu sang anak bahwa perintah itu memiliki surat kontrak. Dengan kata lain, Darmono bisa kembali ke Jawa saat kontrak tersebut habis.
“Aku sudah tahu dan sudah mendapat surat kontrak dari Pak Lurah. Akan tetapi, aku belum mengisinya karena perjanjian dalam surat itu lima tahun,” ungkap Darmono.
“Isilah, Nak.”
“Aku tidak mau, Ibu! Jangankan lima tahun, tidak melihat senyum dan wajah Ibu saja dalam sehari membuatku sedih dan resah. Aku hanya ada Ibu di dunia ini. Maka dari itu, jangan suruh aku pergi, Bu. Jika tetap dipaksa, aku ingin Ibu ikut denganku.”
Darmono bangkit dan melangkah pergi dengan perasaan tidak menentu. Ia yang sangat menyayangi sang ibu karena tidak mendapat kasih sayang dari sang bapak dari kecil, tentu tidak tega pergi sendiri. Dalam setiap langkah, ia memikirkan cara untuk tidak berpisah dengan sang ibu. Jika perintah bisa dilawan, tentu Darmono akan melawannya.
Tiga hari bermusyawarah, akhirnya Darmono mendapat angin segar. Pak Lurah berjanji akan mengikutsertakan Sakdah pada rombongan kedua yang rencana dilakukan setelah rombongan pertama pergi selama enam bulan. Tentu rombongan pertama yang dikirim kaum pria, mengingat dan menimbang tujuan utama dari transmigrasi itu sendiri memindahkan penduduk ke sebuah tempat atau pemukiman baru dan membuka lahan baru yang belum dijajaki oleh manusia.
Hari Sabtu, Sakdah mengantar Darmono ke balai desa. Wanita itu pergi ditemani oleh teman masa kecil sang anak yang bernama Wirna. Tentu Wirna bukan sekadar sahabat, melainkan orang yang disukai oleh Darmono sejak sepuluh tahun yang lalu dan telah menjalin hubungan enam bulan yang lalu.
“Dek Wirna, aku minta tolong kepadamu untuk menjaga Ibu. Aku berjanji akan mengirim surat setiap bulan untuk bertukar kabar,” ucap Darmono dengan sopan.
“Iya, Mas,” jawab Wirna, lalu tersenyum senang.
Setelah itu, Darmono melihat dan mengusap wajah sang ibu dengan lembut. Ia memeluk Sakdah dengan kuat, seolah-olah tidak ingin dilepaskan lagi. Tentu Darmono menahan rasa sesak dan tangis agar sang ibu tidak ikut-ikutan sedih. Lalu, ia melepaskan pelukan itu.
“Ibu, jaga diri baik-baik. Yang pergi hanyalah raga, bukan rasa sayangku kepada Ibu,” ungkap Darmono, lalu mencium berkali-kali punggung tangan Sakdah.
“Iya, Nak. Kamu baik-baik di sana. Jangan lupa makan, salat, dan mengaji.” Sakdah megusap pelan rambut Darmono. Air mata yang sudah ditahan, akhirnya keluar, membuat pipi Sakdah basah. Wanita itu harus merelakan sang anak pergi ke pulau seberang walaupun hatinya menjerit pilu.
Pascaperang dan Kemerdekaan Negara Indonesia, pertumbuhan ekonomi dan sosial masih gonjang-ganjing, maka program transmigrasi pada saat itu tidak memungkinkan. Karena kebijakan tersebut, Darmono yang baru dua bulan menetap di Lampung, berencana kembali ke Pulau Jawa setelah berdiskusi dengan pemerintah setempat. Alhasil, ia dibolehkan pulang setelah setahun kerja di sana. Tentu Darmono mengirim surat kepada Wirna agar sang ibu tidak pergi ke lampung sesuai dengan perjanjian awal.
Selama di Lampung, Darmono dan pemuda-pemuda lain bekerja dengan keras. Mereka membuka lahan baru, tempat baru, dan bertemu dengan orang-orang baru. Kendati demikian, rasa rindu masih bergejolak untuk segera dituntaskan. Di dalam salat, Darmono selalu menyampaikan keluh kesah kepada Tuhan Yang Maha Esa, meminta agar sang ibu diberi kesehatan dan umur yang panjang. Tentu ia ingin Tuhan mengizinkan dirinya untuk bertemu dengan sang ibu dan juga Wirna.
-Selesai-
Indonesia, 25 Januari 2023
Naskah cerpen ini juara satu dalam lomba even nasional yang diselenggarakan oleh Katakata grup Facebook dengan tema transmigrasi.

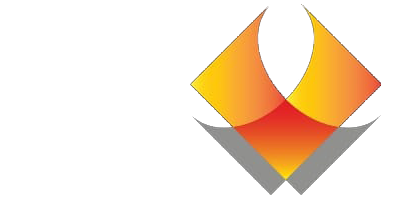



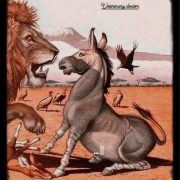









Comments