Buku ini termasuk buku yang berbeda dari kebanyakan buku lainnya. Alasannya yaitu pertama, apa yang disampaikan oleh Buya Syafii tidak lain adalah orasi ilmiah yang disampaikan dalam acara Nurcholish Madjid Memorial Lecture (NMML) yang dilaksanakan oleh Universitas Paramadina pada tahun 2009 lalu. Yang kedua, selain pandangan yang disampaikan oleh pembicara utama, bangunan buku ini juga diperkuat dengan beberapa komentator yang menanggapi, mengkritik atau bahkan menyampaian sudut pandang lain terkait politik identitas dan masa depan pluralisme Indonesia. Dengan latar belakang dan pemikiran yang beragam para penanggap ini, menjadikan buku ini menjadi bacaan yang berbobot dan kaya akan pemikiran dan pandangan. Yang ketiga, pada BAB terakhir Buya Syafii juga kembali menanggapi para komentator. Beragamnya pemikiran dan pandangan para penanggap dan adanya saling kritik-mengkitisi, membuat buku ini sangat dilayak dibaca dan ditelaah oleh banyak kalangan, terutama yang fokus pada kajian politik identitas dan pluraslime.
Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Indonesia (Buya Syafii Maarif)
Politik identitas mulai dilirik ilmuan sosial pada tahun 1970-an. Bermula di Amerika Serikat ketika kelompok minoritas merasa terpinggirkan dan merasa teraniaya. Pada fase awalnya, kelompok yang merasa teraniaya cakupannya hanya permasalahan gender, ras, etnisitas, namun perkembangannya meluas hingga permasalahan agama, kepercayaan dan ikatan-ikatan kultural lainnya.
Menurut Buya, Politik Identitas di Indonesia berkaitan dengan masalah etnisitas, ideologi, agama dan kepentingan-kepentingan lokal. Pemekaran wilayah menurutnya dapat dipandang sebagai salah satu wujud politik identitas. Isu-isu yang diangkat adalah tentang keadilan dan pembangunan. Pertanyaannya adalah apakah politik identitas ini akan membahayakan posisi nasionalisme dan pluralisme? Jika berbahaya, dalam bentuk apa dan bagaimana cara mengatasinya?
Politik Identitas : Kerangka Teori dan Bentuk Praktisnya di Berbagai Kawasan
Buya mengutip pandangan L.A Kauffman dalam menjelaskan hakikat politik identitas. Asal muasalnya adalah adanya gerakan mahsiswa anti-kekerasan yang dikenal dengan SNCC (the Student Nonviolent Coordinating Committee), sebuah gerakan yang memperjuangkan hak-hak sipil di Amerika Serika tahun 1960-an. Secara subtanstif, politik identitas dikaitkan dengan kepentingan anggota kelompok sosial yang merasa diperas dan tersingkir dari dominasi arus besar dalam sebuah bangsa dan atau Negara. Di Amerika Serikat, isu ini berkembang di masyarakat kulit hitam dan masyarakat berbahasa spanyol yang terpinggirkan oleh roda kapitalisme yang pemilik modalnya umumnya dikuasai oleh masyarakat kulit putih (L.A Kaufman, The Anti-Politics of Identitiy, Socialist Review, No.1 Vo. 20, Jan-March 1990, hal 67-80).
Adapun bentuk ekstrem dari politik identitas adalah gerakan separatisme. Ini terlihat seperti yang terjadi di Quebeck, sebuah wilayah di Kanada yang berbahasa Perancis.
Secara hisoris, Indonesia sebagai sebuah bangsa, baru dibentuk pada tahun 1920-an. Pertama dilakukan melalui kegiatan PI (Perhimpunan Indonesia) di Belanda dan dilaksanakannya Sumpah Pemuda 1928. Menurut buya, Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman budaya (plural). Politik identitas yang sering muncul ke permukaan harus ditangani secara bijak. Modal dasar untuk pengawalan keutuhan bangsa adalah pengalaman sejarah berupa pergerakan nasional, PI, Sumpah Pemuda, Pancasila dan adanya tekad bulat untuk mempertahankan dan membela keutuhan bangsa dan negara ini. Dalam ranah gerakan sosial keagamaan, Indonesia mempunyai Muhammadiyah dan NU, sebagai sayap dan telah mengukuhkan dirinya sebagai benteng demokrasi dan pluralisme di Indonesia. Walaupun seringkali digerogoti oleh kelakuan politisi, namun Indonesia masih bisa bertahan.
Tantangan yang cukup serius terhadap keutuhan bangsa datang dari berbagai sempalan agama dengan politik identitasnya masing-masing (buya menggunakan istilah “sempalan”), yang anti-Pancasila, anti-demokrasi dan anti-pluralisme. Bentuk ekstremnya yaitu aksi bom bunuh diri dan aksi-aksi terorisme yang berjeraring dengan kelompok transnasional Al-Qaeda.
Selain politik identitas yang bermuatan etnisitas, agama dan ideologi politik, Indonesia juga berhadapan dengan RMS (Republik Maluku Selatan), GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dan GPM (Gerakan Papua Merdeka), sebagai perwujudan dari kegelisahan etnis-etnis ini dari politik sentralistik Jakarta. Gerakan DI (Darul Islam) juga menggunakan agama sebagai payung ideologi politik identitas mereka. Namun, gerakan-gerakan politik identitas diatas, rekatif masih dapat diatasi dengan militerisme dan diplomasi persuasif.
Beralih ke realitas politik Indonesia kontemporer, yang menjadi burning issues terkait politik identitas adalah munculnya gerakan radikal atau setengah radikal yang berbaju Islam di Indonesia. Gerakan ini mengkampanyekan anti demokrasi dan anti pluralisme, bahkan sampai pada batas yang jauh yaitu anti nasionalisme. Menurut buya, secara ideologis gerakan ini mendapat inspirasi dari gerakan islamis dan salafi yang semula berpusat di negara-negara arab.
Walaupun gerakan islami dan salafi ini terdiri dari berbagai faksi di Indonesia, dalam satu hal mereka punya tuntutan yang sama yaitu : pelaksanaan Syariah Islam dalam kehidupan bernegara. Buya menyebutkan, faksi-faksi yang dibicarakan adalh MMI (majelis Mujahidin Indonesia), FPI (Front Pembela Islam) dan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia). Semua faksi bersikeras untuk pelaksanaan Syariah dalam kehidupan bernegara. MMI misalnya sangat menyesalkan tersingkirnya Piagam Jakarta yang berbunyi “dengan kewajiban menjalankan Syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, pada 18 Agustus 1945 . Bagi MMI, penolakan arus besar umat islam Indonesia terhadap pelaksanaan syariah secara konstituisonal dengan sendirinya dapat masuk dalam kategori “kafir, fasiq dan zalim”.
FPI yang didirikan pada 17 Agustus 1998 di Pesantren Al-Umm Ciputat, Tanggerang, berdasakan latar belakangnya dilahirkan karena adanya anggapan bahwa Umat Islam telah lama menjadi korban penindasan, seperti di Aceh, Lampung, Tanjung Priok, Haur Koneng dan Sampang, tetapi tidak terungkap dan tidak mendapat keadilan. Kelompok ini tercatat telah melakukan tindak kekerasan atas nama agama terhadap gereja, Ahmadiyah dan kelompok lain. Menurutnya, segala tindakan itu dinilai sebagai bagian dari prinsp nahi munkar (mencegah kemungkaran). Menurut buya, perbuatan itu adalah tindakan kekerasan itu dilakukan dengan cara-cara yang munkar oleh aparat swasta,
Dalam memandang HTI, buya menjelaskan : HTI berbeda dengan MI dan FPI yang bercorak lokal Indonesia. HTI adalah gerakan politik transnasional yang pertama kali digagas antara lain oleh Taqiyuddin al Nabhani, sempalan dari al ikhwan. Tujuan akhir dari perjuangan politik mereka adalah terciptanya sebuah kekhalifahan yang meliputi seluruh dunia islam dibawah satu payung politik. Bagi HTI, khilafah adalah satu-satunya sistem politik yang sejalan dengan kehendak syariah.
Menurut tokoh HTI (buya mengutip Farid Wadjdi), demokrasi dengan prinsip kedaulatan rakyat adalah sistem kufur, bertentangan dengan ssstem Islam dan tidak lain tidak bukan adalah hasil rekayasa penjajah yang kafir. Pertanyaannya, mengapa HTI menutup mata terhadap praktik busuk “kekhalifahan” dalam periode sejarah Muslim? Bukankah sistem ini telah melanggar prinsip egalitarian yang diakui dalam demokrasi?
Kesimpulan Buya
Politik Identitas dalam bentuk apapun tidak akan membahayakan keutuhan bangsa dan negara Indonesia dimasa depan, selama cita-cita para pendiri bangsa tentang persatuan dan integrasi nasional, semangat Sumpah Pemuda yang telah melebur sentimen kesukuan, dan Pancasila sebagai dasar fisologi negara tidak dibiarkan tergantung diawang-awang, tetapi dihayati dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab Kesungguhan dan tanggung jawab inilah yang sering dipermainkan oleh orang-orang yang larut dalam pragmatisme politik yang tuna moral dan tuna visi.
Sumber Gambar : https://www.qureta.com/post/belajar-kehidupan-pluralisme-agama-dari-orang-ambon

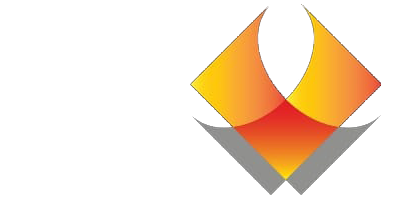










Comments