KETIKA jurnalisme dibungkam, media sosial harus bicara. Karena bila jurnalisme bicara tentang kepentingan, media sosial bicara dengan kekinian. Fakta-fakta bisa disetir, di-setting dan diakomodasi untuk kepentingan kelompok tertentu, tapi kicauan di media sosial mampu memunculkan perlawanan. Jurnalisme terikat dengan kepentingan bisnis, tapi media sosial muncul karena tagar-tagaran yang politis. Menutupi fakta adalah tindakan politik, menutup akses ke media sosial adalah perbuatan paling bodoh yang bisa dilakukan manusia dimuka bumi.
Media sosial hidup dalam keseharian. Di dalam sejarah perkembangan internet yang relatif panjang, perlawanan melalui media sosial akhirnya menemui jalannya sendiri, ditengah hiruk pikuk program-program TV seperti ILC, Mata Najwa hingga Rumah Uya. Rekayasa media massa dengan sendirinya akan ditolak kaum millennial, tetapi media sosial yang dengan menviralkan tagar-tagar kritis, dari #2019gantistatus hingga #kamibersamamantan, dari detik ke detik memunculkan dirinya, bicara dalam bahasa yang dipahami kaum millennial. Jangan baper, ini bukan mempopulerkan para influencer dan pegiat media sosial, ini hanya menunjukan eksistensi media sosial. Setiap kali postingan seorang pegiat media sosial di report/banned, beribu kicauan akan dirintis oleh jutaan influencer lainnya, yakni siapapun mereka yang “dikutuk” memiliki jutaan follower dan paket internet berlebih.
Pendekatan media sosial mutakhir selalu menolak terhadap caption yang tidak ada hubungan sejarah dengan fotonya. Pernyataan ini bisa jadi ada benarnya. Meskipun foto yang di-posting sangat instagramable, ketika caption yang di-post tidak sesuai, bisa saja memancing reaksi yang tidak diinginkan dari netizen yang budiman. Sebaliknya, foto yang sangat instagramable dan ditopang dengan caption–caption memukau ala tere liye dan fiersa besari, bukan tidak mungkin menjadi viral dan akan muncul parodi-parodinya yang sangat bagus.
Dengan demikian, latar belakang lahirnya suatu postingan/kicauan menjadi penting dan sangat relevan, jika dihubungkan dengan jumlah follower, jumlah hater dan laju endorsements. Memang harus diakui, latar belakang itu bisa saja ditujukan untuk pamer jalan-jalan, makan dan jam tangan baru. Postingan Attha Halilintar, Ria Ricis, Tretan Muslim hingga Young Lex mungkin disukai ribuan follower, tetapi riwayat caci maki dan baku hantam di kolom komentar tak kalah menariknya – dan kedua hal itu harus dihubungkan. Karena, banjir komen dipostingannya justru menghidupkan suasana diskursus yang konstruktif.
Meski begitu, latar belakang lahirnya suatu postingan bisa menjadi tidak penting, jika itu dimaksud sebagai sebuah ajang pamer. Dalam momentum yang bagaimana suatu postingan bisa lahir seperti itu? Namun, toh harus dikatakan juga, bahwa meski lahirnya suatu postingan bisa dibaca melalui riset ilmiah, prosesnya itu sendiri tetap tidak jauh dari ajang pamer dan pansos. Bahkan, saya kira, itulah tujuan sang tukang posting.
Sekali lagi, jurnalisme dibungkam, bisakah media sosial bicara?
* Plesetan ”Jurnalisme Dibungkam, Sastra Harus Bicara” Karya Seno Gumira Ajidarma

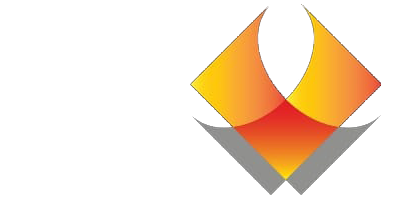








Comments