Sudah menjadi rahasia umum jika kehidupan bermasyarakat di tengah keragaman Indonesia tidak selalu berjalan mulus. Selalu ada konflik yang mencuat akibat adanya sentimen antar golongan. Utopia kedamaian di tengah keberagaman yang dimimpikan Pancasila nampak semakin jauh untuk diraih jika melihat kondisi intoleransi antar agama di Indonesia.
Indonesia merupakan negara dengan enam agama resmi dan banyak kepercayaan lokal yang tersebar di penjuru wilayahnya. Populasi agama terbesar di Indonesia merupakan muslim dengan jumlah lebih dari 229 juta manusia yang setara dengan 13% populasi muslim dunia. Keragaman dan ketimpangan jumlah penganut agama ini seringkali menjadi penyebab konflik agama di Indonesia.
Kebebasan beragama sudah termaktub pada banyak pasal salah satunya Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya. Namun pada implementasinya, fakta yang kontras justru ditemukan di lapangan.
Laporan dari BBC News yang menyebutkan dalam sepuluh tahun terakhir terdapat setidaknya 200 gereja disegel dan ditolak warga. Tirto.id, salah satu portal berita daring juga menyebutkan hal serupa. Dalam publikasinya berjudul Kasus Intoleransi Terus Bersemi Saat Pandemi terdapat banyak praktek intoleransi pada umat minoritas selama masa pandemi.
Beberapa kasus yang teridentifikasi sepanjang 2020 adalah jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Kota Serang Baru yang diganggu saat beribadah pada 13 September, sekelompok warga Graha Prima Jonggol menolak ibadah jemaat Gereja Pantekosta Bogor pada 20 September, umat Kristen di Desa Ngastemi dilarang beribadah oleh sekelompok orang pada 21 September, dan larangan beribadah terhadap jemaat Rumah Doa Gereja GSJA Kanaan di Kabupaten Nganjuk pada 2 Oktober.
Bukan hanya dilarang beribadah, terdapat pula kasus surat edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan instruksi seluruh siswa SMA/SMK untuk wajib membaca buku Muhammad Al-Fatih 1453 karya Felix Siauw. Meskipun akhirnya surat edaran tersebut dibatalkan satu hari setelahnya, kejadian ini menyulut emosi banyak pihak dan menjadi pemicu timbulnya pertanyaan tentang seberapa banyak kasus intoleransi yang tidak terekspos ke permukaan?
Jika ditarik ke belakang, kasus intoleransi agama bukan hal baru dan sudah menjadi pekerjaan rumah lama. Kasus-kasus perpecahan agama seperti konflik umat Kristen dan muslim di Poso pada akhir tahun 90-an, konflik Ambon pada 1999 yang diawali pemalakan pemuda muslim pada warga nasrani yang kemudian menyebar dan membakar amarah, konflik Tolikara yang terjadi karena umat Gereja Injil Indonesia menyerang umat Islam yang sedang shalat Idul Fitri di Markas Korem di Tolikara dan aparat keamanan tidak berdaya menghadapi massa Gidi, hingga konflik Situbondo pada 1996 akibat warga yang tidak puas atas hukuman yang diberikan kepada seorang penista agama islam.
Bagai gajah di pelupuk mata yang tidak nampak, intoleransi dan diskriminasi agama ini bagaikan angin lalu yang tidak digubris dengan pelaku dibiarkan tanpa diadili. Muncul kekhawatiran ketika kondisi ini terus berulang, orang-orang akan menganggapnya hal yang normal. Padahal sebagai warga negara Indonesia, bukankah kedudukan semuanya sama dan tidak ada hirarki pada agama?
Tak perlu menunggu penegakan hukum menjadi lebih baik, upaya yang berawal dari inisiatif masyarakatlah yang dibutuhkan saat ini. Narasi-narasi heroik yang bernafaskan kemanusiaan untuk mengutuk perbuatan diskriminatif kini harus digaungkan pula di dalam negeri. Tanpa melihat latar belakang suku, agama, maupun golongan. Mari galakkan toleransi atas dasar rasa prihatin, prihatin pada sesama manusia yang lahir bersama di negeri Indonesia.

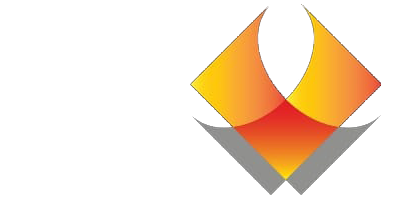











Comments