By Nuraini Chaniago
“Saya harus melahirkan anak pertama kami dengan keadaan prematur dan dengan kondisi mental yang terpuruk” ujar teman perempuanku disela-sela kegiatan.
Beberapa waktu lalu, saya dan beberapa teman melakukan perjalanan dari Padang ke Lampung dengan agenda pelatihan ideologi kepemimpinan nasional se sumatera. Kegiatan ini merupakan agenda Lembaga Hikma dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam menghadapi pilkada yang akan dihelat oleh masyarakat Indonesia beberapa waktu mendatang.
Pelatihan ini menghadirkan peserta se sumatera, diantaranya, Jambi, Palembang, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, dan Lampung sebagai tuan rumah. Di samping itu, pada kegiatan ini juga menghadirkan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yakni bapak Busyro Muqaddas dan mantan ketua KPK, yakni bapak Novel Baswedan. Kegiatan ini berlangsung selama beberapa hari, dengan insight dan pengetahuan yang baru.
Di sela-sela waktu kosong kegiatan, saya dengan dua rekan perempuan kami yang juga merupakan aktivis perempuan di Sumatera Barat, berbincang-bincang random tentang banyak hal, mulai dari masalah politik dewasa ini hingga pengalaman personal yang dialaminya sebagai perempuan Jawa yang tumbuh besar dengan berbagai tradisi Jawa yang menjadikan perempuan lebih rentan menjadi korban dan mengabaikan haknya sebagai manusia utuh.
Teman saya mengungkapkan pengalamannya menjadi perempuan Jawa dengan berbagai tradisi yang membuatnya harus dituntut ini dan itu agar bisa dikatakan sebagai seorang perempuan yang baik dan membawa keberuntungan. Salah satunya ialah, ketika ia menikah dan mengandung anak pertamanya. Berita kehamilan yang sejatinya adalah sebuah berita kebahagiaan bagi calon ibu dan keluarga besar.
Namun tidak bagi teman saya, di awal berita kehamilannya tersebar di keluarga besarnya, pihak keluarga suaminya langsung memberikan tekanan kepadanya, bahwa ia harus melahirkan anak pertamanya laki-laki bukan perempuan. Karena dalam kebiasaan Jawa, katanya, anak pertama laki-laki adalah sebuah keberuntungan dibandingkan anak perempuan. Sampai-sampai mertua perempuannya memaksanya untuk meminum ramuan-ramuan yang menurutnya tak masuk akal setiap hari, agar anak yang dalam kandungannya berjenis laki-laki.
Fase kehamilan yang seharusnya dinikmati dengan banyak cinta dan kasih dari orang-orang terdekatnya, namun harus dilaluinya dengan harap-harap cemas, takut, bahkan sempat keluar masuk rumah sakit akibat drop dan kesehatan mentalnya mulai menurun akibat tekanan yang ia peroleh selama kehamilannya. Ia tak berani melakukan USG untuk mengetahui jenis kelamin anak pertamanya, karena ketakutannya tersebut, hingga ia harus melahirkan anak pertamanya dalam keadaan mental yang sangat terpuruk, kalau tidak bisa dikatakan hancur, hingga ia harus kehilangan satu anak kembarnya yang tidak tumbuh sempurna di dalam rahimnya akibat sang ibu yang stress dan psikis yang porak poranda akibat tekanan akan sebuah tradisi yang tidak memanusiakan perempuan tersebut.
Ini bukan tentang tradisi Jawa semata, karena disetiap daerah tentu punya tradisi masing-masing, namun ini tentang hak dan kemanusiaan perempuan sebagai manusia utuh. Manusia, baik laki-laki maupun perempuan, sama-sama manusia yang memiliki hak untuk hidup layaknya manusia. Begitupun perihal anak, anak laki-laki ataupun perempuan adalah sama-sama manusia setara dan sama-sama membawa berkah, bukan semata-mata ditentukan oleh jenis kelamin.
Sebagai seorang perempuan yang hidup di tengah-tengah masyarakat modern hari ini, perempuan masih saja menjadi bulan-bulanan budaya patriarki dengan berbagai balutannya, yang secara sadar ataupun tidak telah membuat beban perempuan semakin berlipat ganda. Sudahlah menjadi manusia perempuan dianggap sebagai makhluk inferior, ditambah lagi dengan tradisi yang menuntut ini dan itu agar disebut sebagai perempuan yang utuh. Padahal, perempuan dengan kediriannya adalah manusia utuh tanpa embel-embel lainnya.
Kasus teman saya mengajarkan kepada kita, bahwa Indonesia masih saja mengkotak-kotakkan antara laki-laki dan perempuan dari jenis kelamin semata, tanpa melihat kemanusiaan dan kepasitasnya sebagai manusia. Tradisi-tradisi yang di luar nalar itu tak mestinya kita pupuk hingga saat ini, karena jelas hal tersebut hanya membuat perempuan menjadi korban dalam banyak hal, beruntung teman saya memiliki pasangan yang support sistem, jika tidak, maka mungkin saja ia akan melakukan hal-hal yang merugikan dirinya sendiri dan keluarganya.
Maka, mari kita sama-sama menolak bias dan kebiasaan-kebiasaan yang tidak memanusiakan perempuan tersebut. Warisan patriarki yang sudah turun-temurun ini bukan untuk kita rawat apalagi diwariskan kepada generasi selanjutnya, melainkan harus kita putus dari sekarang, serta dimulai dari diri sendiri untuk melihat semua manusia adalah manusia utuh yang memiliki hak dan akses yang sama, serta sama-sama memiliki keberkahan sebagai manusia, laki-laki ataupun perempuan.

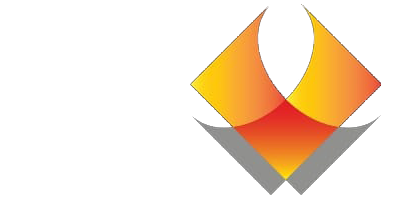











Comments