Agama adalah pedoman hidup yang diberikan Tuhan kepada umat manusia, agar kehidupan mereka di dunia menjadi sejahtera, dan mereka akan selamat kelak di akhirat. Doktrin-doktrin agama bersifat ideal dan menghendaki para pemeluknya mengamalkan doktrin tersebut dalam bentuk yang paling baik. Namun terkadang pengamalannya jauh dari bentuk ideal yang dikehendaki agama tersebut. Seringkali agama manampakkan diri sebagai sesuatu yang berwajah ganda, dalam arti bahwa wujud dari pengamalan ajaran suatu agama berbeda jauh dari ajaran yang sebenarnya diinginkan oleh agama itu sendiri. Semua agama menyerukan perdamaian, persatuan dan persaudaraan. Akan tetapi pada tataran pengamalan, agama menampakkan diri sebagai kekuatan yang garang, beringas, penyebar konflik, bahkan terkadang sampai menimbulkan peperangan.
Indonesia merupakan salah satu negara yang sebagian besar merupakan pemeluk agama Islam. Sekalipun demikian, Indonesia bukanlah negara teokrasi yang menjadikan ajaran Islam sebagai konstitusinya, sebab di samping umat Islam yang merupakan mayoritas, terdapat pula pemeluk agama lain yang juga menjadi pemilik sah negeri ini. Indonesia juga bukan negara sekuler, karena agama dipandang sebagai salah satu modal pembangunan, dan berperan dalam kehidupan sosial bangsa Indonesia. Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang mengakui enam agama sebagai agama yang sah untuk dipeluk oleh warga negaranya, dan masih ada pula kepercayaan lokal yang tumbuh dengan subur di negeri ini. Keenam agama tersebut adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu.
Karena sifatnya yang nomografis, pembicaraan radikalisme dalam perspektif sosiologi berbeda jika dibandingkan pembicaraan radikalisme dalam ilmu politik, yang hanya bertujuan mendeskripsikan dan menjelaskan objek yang sedang diamati, dan tidak bermaksud untuk menyusun suatu kerangka teori guna dijadikan alat atau kerangka bertindak bagi keperluan dan kepentingan praktis sebagaimana yang dipahami oleh ilmu politik. Oleh karena itu, dalam sosiologi fokus pertanyaannya berkisar pada : ”what it is about a society that increases or decreases the likelihood of violence”, dan radikalisme baru menjadi persoalan sosial (social problem) ketika ”violence must also arouse widespread subjective concern”.
Ada dua pendekatan utama dalam memahami radikalisme dari sisi Sosiologi, yaitu perspektif fungsionalisme (functionalist theory), masyarakat dilihat sebagai bentuk keteraturan (order) yang terdiri dari berbagai elemen yang saling bersinergi antara satu dengan lainnya, guna menciptakan keseimbangan (equilibrium). Emile Durkheim adalah salah satu pemikir yang dapat digolongkan sebagai fungsionalis, dan sumbangan pemikirannya terhadap radikalisme (violence) adalah diintrodusirnya konsep anomi, suatu konsep sosiologi yang oleh Emile Durkheim guna menjelaskan kondisi psikologi yang merasa asing (estranged) sebagai akibat tercabutnya atau hilangnya rasa kemanusian dalam ranah kehidupan (uprooted), dan ekonomi menurut Emile Durkheim adalah penyebab yang bisa menimbulkan kondisi anomi tersebut. Melalui pendekatan ini radikalisme dipahami sebagai akibat dari perubahan sosial ekonomi yang tidak diikuti dengan perubahan regulasi sehingga timbul ketimpangan dimasyarakat dlam menghadapi kondisi tersebut.
Berdasarkan teori konflik, radikalisme muncul sebagai akibat adanya pendistribusian wewenang yang tidak merata. Tidak meratanya pendistribusian wewenang berujung pada adanya penumpukan kekuasaan pada satu orang, atau kelompok tertentu, dan dengan kewenangan yang ada, kelompok yang memiliki kekuasaan yang besar tersebut akan cenderung mengguna-kannya untuk mempertahankan kekuasaan yang dimilikinya. Atau dengan kata lain, radikalisme yang dilakukan sebagai upaya mempertahankan dominasi kelompok atas kelompok lainnya.
Berbeda dengan bidang kehidupan lainnya, dalam agama terdapat berbagai ajaran, simbolisme, cerita/amsal, konsep, dogma, pencitraan, ritualitas serta idealitas sistem, dan struktur pribadi maupun sosial yang dikehendakinya, yang menjadikan agama menyentuh seluruh dimensi kehidupan manusia. Mulai dari dimensi alam atas dan alam bawah sadar manusia, dimensi imanensi dan transendental, dimensi psikis dan fisik manusia. Keseluruhan substansi agama tersebut bersifat universal, sedangkan jika menyangkut bagaimana simbol, konsep, ritualitas dan idealitas yang ada pada agama tersebut dipahami oleh pemeluknya, maka agama menjadi bersifat partikular.
Agama ditempatkan sebagai struktur tertinggi dari seluruh tatanan dan sistem sosial manusia dalam perspektif fungsionalisme menjadikan fungsi agama sebagai superstruktur ideologis yang mempengaruhi subsistem lainnya. Sedangkan bagi mereka yang mengkonstruksikan agama dengan latar dialektika materialisme misalnya, memiliki pandangan yang berlawanan dengan fungsionalisme dimana fungsi agama yang tetap diletakkan sebagai superstruktur ideologis akan tetapi sangat ditentukan oleh infrastruktur material dan struktur sosial.
Dari kedudukannya inilah, agama dinilai memiliki fungsi manifes (manifest functions) yaitu fungsi yang disadari betul oleh para partisipan sebagai manifestasi objektif dari suatu sistem sosial, misalnya meningkatkan kehesivitas umat (Ukuwah islamiyah), atau memiliki fungsi laten (latent functions) yaitu fungsi yang tidak dikehendaki secara sadar dari sistem sosial tersebut dalam memunculkan radikalisme, atau menurut Azyumardi Azra agama merupakan lahan empuk untuk menjadi crying banner dalam melakukan tindakan anarkis, yang juga sama-sama didasari pada pembacaan dan konstruksi tekstualitas yang ada dalam agama itu sendiri.
Karena substansi yang ada pada agama itu juga, sehingga agama dengan sangat mudah terseret atau diseret dalam kancah radikalisme dengan menggunakan berbagai bahasa ilmupengetahuan yang ada, misalnya bahasa ideologi, politik, sosial budaya ataupun ekonomi. Anehnya, pada sisi ini sikap dan perilaku umat beragama sering menampakkan diri pada sifat yang ambiguitas dalam memahami teks-teks agama, sehingga berbagai bentuk kegiatan yang merugikan dan menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan yang fitri selalu didasari pada teks agama, padahal tindakan itu dilihat dari sisi ajaran agama yang sama tidak pernah dibenarkan sama sekali.
Samuel Huntington, adalah salah seorang yang mengkhawatirkan hal tersebut. Menurutnya, setelah runtuhnya ideologi Marxis dan negera-negara komunis, maka segera terlihat suatu kecenderungan yang kuat untuk memperlihatkan kembali peranan agama sebagai salah satu faktor yang turut menentukan rasa identitas suatu bangsa, dan lingkaran budaya yang dipegang oleh beberapa bangsa. Kekuasaan ekonomi menurut Huntington masih tetap menentukan aliansi-aliansi regional dimasa depan sesuai dengan dinamika kapitalisme. Namun, lebih lanjut Huntington berpendapat, kekuatan ekonomi tersebut memerlukan dimensi agama guna mempererat aliansi yang dibangun tersebut. Dalam kondisi seperti ini, maka menurut Huntington akan muncul blok yang kuat yang berakar pada Konfusianisme, Agama Shinto, Islam dan ini dinilai olehnya akan mengancam peradaban yang selama ini telah terbangun.
Demikian juga dalam relasinya dengan politik, agama dengan mudah terseret dalam kancah radikalisme dengan dipolitisasinya agama sebagai sumber radikalisme terbuka, yang sebenarnya lebih didasari oleh melemahnya sistem dan institusi politik yang ada. Masih dalam perspektif politik, agama juga sering dijadikan legitimasi radikalisme yang dilakukan oleh penguasa dengan maksud mempertahankan hegemoni kekuasaan.
Secara holistik agama tidak membawa ajaran radikalisme oleh banyak kalangan disadari betul kebenarannya, halini tentunya jika dikaitkan dengan eksistensi diturunkannya agama bagi manusia. Ber-bagai moralitas yang sifatnya transenden dari agama sejatinya berimplikasi ke dalam imanensi kehidupan manusia. Hadirnya moralitas yang sifatnya transendental ini sejatinya diaktulisasikan ke dalam dimensi kemanusiaannya secara utuh sebagai makhluk rasional, dan spiritual. Sehingga kedamaian, ketenangan, dan kesejahteraan dapat terwujud secara kukuh dalam ke-hidupan ini. Namun demikian, kiranya tidak bisa juga dipungkiri bahwa dalam agama, secara tekstual ditemukan teks-teks yang bisa memberikan nuansa radikalisme.
Tekstualitas tersebut bisa muncul dalam bentuk ajaran, simbolisme, cerita, konsep, dogma, pencitraan, ritualitas serta idealitas sistem dan struktur pribadi maupun sosial yang dikehendaki oleh agama. Semua substansi tersebut dalam bentuknya yang tentunya bersifat netral, dan ketika semua substansi tersebut ingin dimanifestasikan dalam dunia, dan bermakna, maka intervensi manusia dalam bentuk penafsiran diperlukan.
Persoalan penafsiran atas teks-teks keagamaan inilah, yang menurut penulis dinilai menimbulkan justifikasi radikalisme atas nama agama. Mulai dari radikalisme domistik (domestic violence) yang sulit untuk dideteksi, sampai radikalisme pada ranah publik (public violence).Sebagai contoh pada radikalisme domestik, dalam al-qur’an terdapat teks-teks yang kiranya bisa ditafsirkan memberikan justifikasi pada radikalisme itu sendiri, misalnya kata ”idlrih hunna” dalam surat An-Nisa ayat 3 oleh departemen agama diterjemahkan dengan ”pukullah mereka”. Pengertian ini menurut Nassaruddin Umar tidak salah, tetapi kata tersebut tidak mesti diartikan demikian. Dengan menunjuk pada kamus bahasa Arab Nassaruddin memberikan pengertian bahwa kata tersebut (dlaraba) sebagai”gauli atau setubuhilah” dan terjemahan ini lebih sesuai dengan fungsi dan tujuan perkawinan untuk menciptakan ketenteraman dan kasih sayang. Demikian juga menyangkut pelarangan seorang perempuan/wanita untuk menjadi pemimpin, yang sudah dinilai sebagai bentuk radikalisme politik, merupakan persoalan bagaimana penafsiran atas teks-teks tersebut dilakukan.
Mencontoh pada persoalan tersebut di atas, maka persoalan yang utama dalam melihat bagaimana radikalisme yang dilakukan mendasarkan pada agama adalah persoalan bagaimana menafsirkan teks-teks agama, apakah ada makna objektif dari teks itu sendiri, apalagi pada teks-teks agama dimana bahasa Tuhan yang termuat dalam kitab suci merupakan makna sacra yang dicoba diterapkan dalam dunia profan manusia. Oleh karena itu dalam memahami teks-teks agama tidaklah cukup dengan melakukan interpretasi secara tekstual saja tetapi diperlukan juga interpretasi kontekstual. Karena dalam interpretasi tekstual pendekatan yang digunakan lebih bersifat formalistik-legalstik, yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada teks-teks yang dipahami dalam dimensi transendental semata, sehingga bisa lepas dari konteks kesejarahan, baik dalam konteks kedahuluan, kekinian maupun keakan-datangan. Interpretasi tekstual yang bersifat formalistik-legalistik ini oleh Muhammad Arkoun disebut sebagai pendekatan monolitik, sedangkan interpretasi kontekstual adalah suatu metode interpretasi yang melihat agama dalam dimensi kehidupan yang lebih luas, baik dalam konteks kesejarahan maupun pesan zaman dijadikan pilar utama dalam melakukan interpretasi teks agama.
Sumber: Angga Natalia, M.I.P adalah dosen Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung. Alumni Program Studi Ilmu Pemerintahan Pascasarjana Universitas Lampung

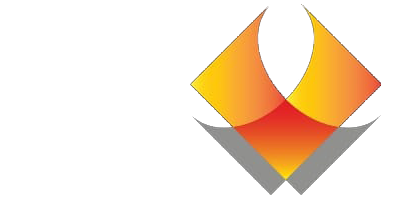













Comments