Minuman beralkohol sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Indonesia memiliki sejarah panjang dengan minuman fermentasi tersebut. Beberapa daerah seperti Bali, Lombok, Sulawesi, Semarang, Banyumas, dan lainnya juga memproduksi kearifan lokal minuman tersebut.Budaya minum muncul seiring dengan hadirnya ragam minuman fermentasi di Nusantara yang diyakini sebagai salah satu warisan kebiasaan nenek moyang. “Minuman fermentasi adalah wujud nyata antara kekayaan alam dan kekayaan budaya yang ada di Nusantara,” ujar antropolog Universitas Indonesia, Raymond Michael Menot seperti dilansir oleh CNNIndonesia.com pada 13 November 2020.
Prasasti Pangumulan (902 M), menuliskan tuak sebagai minuman yang disajikan dalam upacara penetapan tanah sima. Prasasti ini ditemkan di Desa Kembang Arum, Klegung, DI Yogyakarta.
Catatan sejarah kedua pada Serat Ma Lima pada 1903. Serat yang dianggap sebagai falsafah hidup orang Jawa ini merujuk pada berbagai larangan, termasuk larangan mabuk atau moh mendem. Selain itu Kitab Negarakertagama mengungkapkan bahwa tuak dan arak selalu ada dalam tiap perayaan di Majapahit.
Demikian pula dengan serat centhini Suluk ini mengisahkan 10 tingkatan mabuk minuman beralkohol disertai penggambaran reaksinya.
Selain dalam kitab dan serat, perkara minuman beralkohol juga ditemukan dalam tarian. Tarian beksan inum di lingkungan Kadipaten Pakualaman ini ditampilkan oleh 4 penari pria menggunakan botol minuman dan 2 sloki.
Beksan Sekar Madura (Beksan gendul), tarian di lingkungan Kasultanan Ngayogyakrta Hadiningrat juga menggunakan properti botol minuman dan gelas sloki dalam tariannya.
Raymond juga menemukan bahwa minuman fermentasi menjadi tradisi di kebanyakan wilayah pesisir sebagai cara masyarakat beradaptasi dengan iklim.
“Di udara berangin, minuman itu (fermentasi) muncul,” kata dia.
Fermentasi, kata Raymond, merupakan cara pembuatan air minum yang paling tua. Seiring masuknya budaya baru, istilah distilasi pun muncul. Nama terakhir ini merupakan teknik lain pembuatan minuman beralkohol, yang menurut Raymond, terpengaruh oleh budaya China dan Eropa yang datang ke Nusantara. Alhasil, ragam minuman fermentasi dan distilasi tradisional mewarnai aneka kearifan lokal dari Sabang sampai Merauke.
“Minum tidak bisa disebut sebagai penyimpangan. Tapi itu bentuk kontinyuasi dari yang dulu pernah ada,” ujar antropolog Universitas Indonesia, Semiarto Aji Purwanto yang dilansir lewat CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu.
Sejarah mencatat, kebiasaan minum telah hadir lama sebelum Indonesia menjadi bangsa. Catatan itu dibuktikan dalam naskah Nagarakretagama (1365) yang ditulis pada masa keemasan Kerajaan Majapahit abad ke-14. Dalam naskah itu dikisahkan, minuman beralkohol seperti tuak nyiur, arak kilang, dan tuak rumbya menjadi hidangan utama sebuah jamuan. Minuman-minuman itu ditaruh dalam sejumlah porong dan guci.
Salah satunya dilakukan Sri Raja Kertanegara, raja terakhir pemimpin Singasari, kerajaan Hindu (Siwaisme)-Budha di Nusantara. Dalam naskah yang sama, sebagai seorang Tantrayana, Kertanegara dikisahkan menjalani tradisi pemujaan yang merujuk pada hal-hal bersifat destruktif atau hedonisme dalam bahasa yang lebih kekinian. Ragam ritual yang hadir pun tak lepas dari pelbagai kebiasaan seperti minuman beralkohol dan seks demi pencapaian nirwana.
Dalam tradisi Hindu-Budha, tuak dan arak punya posisi penting, sebagaimana yang tampak pada masyarakat Dayak-Kaharingan hingga saat ini, misalnya, yang memiliki minuman Baram. Minuman fermentasi beras khas Kalimantan Tengah itu tak cuma menjadi bagian dari identitas, tapi juga terkait hal-hal yang bersifat kultural dan mitologis. Baram digunakan dalam upacara Tiwah, ritual mengantarkan jiwa atau roh manusia yang telah meninggal dunia menuju tempat yang dituju.
“Minuman jadi hal penting dalam penyusunan konteks kebudayaan,” kata Aji.
Beda dulu, beda sekarang. Seiring berjalannya waktu, minuman fermentasi dan distilasi beserta kebiasaan minum yang pernah merona di masa lalu kian mengalami pergeseran makna.
Di beberapa daerah, termasuk Jawa, minuman beralkohol berubah dari sesuatu yang sakral menjadi yang profan. “Jelas ada perubahan. Minum arak sangat berfungsi di masa Kertanegara, tapi makin ke sini, fungsinya berubah,” jelas Aji.
Perubahan itu dibuktikan oleh beberapa catatan literatur yang menggambarkan budaya minum yang berubah menjadi sebentuk hedonisme dan proses pembaratan.
Kuntowijoyo dalam Raja, Priyayi, dan Kawula: Surakarta 1900-1915, misalnya, mencatat kegemaran Pakubuwana X di Kasunanan Surakarta melakukan kundisi-dalam bahasa Inggris berarti ‘toast’-dengan residen-residen pada zamannya. Juga Anak Bangsawan Bertukar Jalan, ketika Budiawan mencatat kebiasaan dansa-dansi serta pesta yang merasuki kehidupan Pura Pakualaman saat kepemimpinan Pakualam IV.
Namun, Aji menampik perubahan makna budaya itu disebabkan kehadiran Belanda di Nusantara. Menurutnya, perubahan itu terjadi tepat setelah Islam membawa pengaruh luas di tanah Jawa, apalagi dengan kehadiran Kesultanan Mataram Baru.
“Jadi kesannya hedonis, seolah-olah itu terjadi karena kedekatan mereka dengan Belanda. Padahal tidak,” kata Aji.

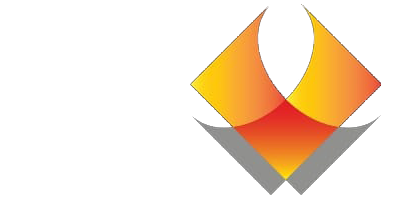











Comments