Penulis Nurrochman
Tahun 2021 menghadirkan pelajaran penting bagi bangsa. Di tengah suasana pandemi, praktik intoleransi tidak pernah surut. Saban hari, ruang publik kita dijejali narasi provokasi, kebencian, dan adu-domba. Memasuki tahun 2022, kita dihadapkan pada pertanyaan krusial ihwal agenda bangsa ke depan. Jika melihat realitas kiwari, agenda bangsa yang paling krusial di tahun 2022 ialah meneguhkan toleransi dan moderasi beragama. Bangsa ini tidak akan menjadi bangsa maju dan beradab selama persoalan toleransi dan radikalisme agama masih menjadi problem laten.
Toleransi sebenarnya telah menjadi karakter bangsa. Catatan sejarah, etnografi dan antropologi Nusantara umumnya memiliki benang merah yang sama. Yakni bahwa masyarakat Nusantara dicirikan dengan karakternya yang toleran, inklusif, dan humanis. Masyarakat Jawa misalnya mengenal ungkapan “tepo seliro”. Yakni keyakinan bahwa setiap manusia harus memperlakukan orang lain sebagaimana ia ingin diperlakukan.
Masyarakat Jawa juga mengenal istilah “sak podo-podone manungsa” yang bermakna bahwa manusia itu setara. Pandangan ini sudah dikenal jauh sebelum Eropa mengenal humanisme. Hampir seluruh komunitas masyarakat di Nusantara memiliki kearifan lokal yang menjunjung tinggi toleransi dan kemanusiaan. Maka, problem intoleransi dan kekerasan yang dilatari primordialisme dan fanatisme agama, mengindikasikan bahwa kita tengah mengalami semacam sindrom kegalauan identitas.
Sindrom Kegalauan Identitas
Kita mengalami kegalauan identitas antara keindonesiaan, kesukuan, dan keagamaan. Sentimen kesukuan dan fanatisme keagaman itulah yang menyuburkan praktik intoleransi. Satu kelompok tega berbuat kekerasan pada kelompok lain hanya karena berbeda suku dan agama. Selain itu, banyak umat beragama alergi pada identitas keindonesiaan, lantas melabeli dirinya dengan identitas baru bertendensi keagamaan. Seolah-olah menjadi umat beragama yang kaffah itu hanya bisa diwujudkan dengan membuang identitas keindonesiaan dan bersikap intoleran.
Padahal, toleransi merupakan bagian inheren Islam. Islam menyebut toleransi dengan tasamuh yang secara harfiah berarti kemudahan. Dari tafsiran itu, toleransi bisa dimaknai sebagai tindakan memudahkan urusan orang lain, termasuk dalam beribadah dan mengekspresikan kesalehan di muka publik. Namun demikian, toleransi idealnya tidak berhenti pada sikap menghargai dan menghormati. Lebih dari itu, toleransi ialah mengafirmasi entitas lain. Tanpa afirmasi, yang ada hanyalah toleransi semu (pseudo-tolerance).
Sikap afirmatif itu disokong oleh setidaknya tiga hal. Pertama, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Di dalam Islam, pengharganaan terhadap HAM ini termaktub salah satunya dalam khutbah Nabi Muhammad pada momen haji perpisahan (wada’). Di dalam Islam, hak hidup manusia ialah harga mati yang tidak boleh ditawar. Inilah prinsip dasar humanisme ala Islam. Maka, jika kita membela kaum minoritas yang tertindas, pada dasarnya kita tidak sedang membela identitas atau ideologinya. Namun, kita membelanya sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat mulia.
Kedua, kesediaan untuk mengenal dan mau bekerjasama dengan entitas lain yang berbeda. Disinilah pentingnya dialog antar-agama berbeda yang dilakukan dalam bingkai sosiologis. Jadi, bukan dialog antar-agama untuk mencari siapa yang memiliki konsep teologis paling kuat dan benar. Namun, dialog untuk mencari solusi pemecahan atas problem bersama seperti kemiskinan, kebodohan, dan sejenisnya. Di titik ini, umat beragama bisa bertemu dalam satu konsensus bersama tanpa menodai spirit akidahnya masing-masing.
Pergeseran Paradigma; Konservatisme ke Moderatisme
Ketiga, komitmen untuk memoderasi cara pandang dan praktik keagamaan. Moderasi beragama ialah upaya merevisi praktik keagamaan yang ekstrem dan didominasi oleh nalar kebencian terhadap agama lain. Selama ini, ada kecenderungan bahwa kesalehan beragama kerap menimbulkan sikap over-reaktif dalam menyikapi perbedaan. Klaim kebenaran atas tafsir agama lantas menjadi alat untuk menjustifikasi tindakan intoleran dan kekerasan terhadap kelompok lain. Paradigma keagamaan yang demikian ini mutlak perlu direvisi.
Pergantian tahun ialah sebuah keniscayaan. Namun, pergeseran paradigma keagamaan butuh perjuangan. Perlu sinergi bersama untuk mempromosikan toleransi dan moderasi beragama. Di level struktural pemerintah perlu menyinergikan seluruh instansi dan lembaga untuk memastikan hak dan kebebasan beragama terpenuhi bagi seluruh warganegara. Pekerjaan rumah terberat ialah menjamin hak-hak kaum minoritas agama yang masih kerap mendapatkan tindakan intoleransi, diskriminasi, bahkan persekusi karena identitasnya.
Sedangkan di level kultural, lembaga pendidikan, ormas keagamaan dan para tokoh agama serta kaum intelektual idealnya berjejaring untuk mengubah mindset atau paradigma keagamaan dari nalar konservatisme ke moderatisme. Cara pandang moderat dalam beragama akan membuka jalan bagi praktik keberagamaan yang inklusif dan toleran.

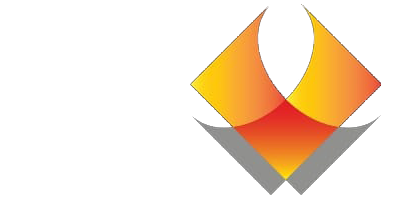










Comments